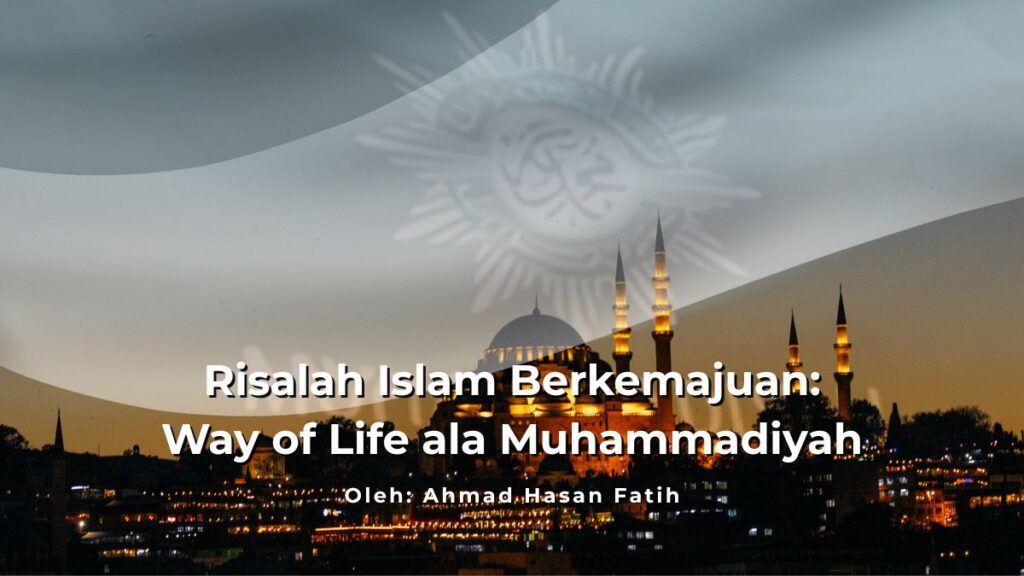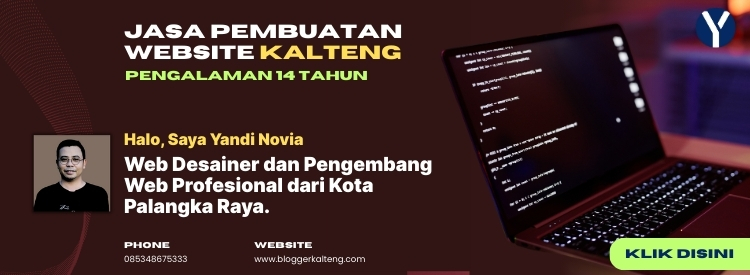Pada sebuah pemukiman sempit di pinggiran kota, seorang ayah tampak duduk di depan rumah, menyalakan sebatang rokok kretek. Asapnya mengepul tinggi, seolah sedang menari-nari di udara sore itu. Dari dalam rumah, terdengar suara anak kecil merengek, dan keluhan dari seorang istri, “Ayah, beras habis.” Lelaki itu hanya terdiam, menatap ke arah langit dengan tatapan kosong, lalu kembali menghisap rokoknya.
Pemandangan tersebut, mungkin bagi sebagian orang tampak sepele. Namun, dibalik kepulan asap rokok itu, ada kisah menyakitkan tentang sebuah prioritas yang salah kaprah. Tentang sosok laki-laki yang lebih takut kehabisan bahan hisapan nikotin daripada kehabisan beras. Tentang keluarga yang harus menahan rasa lapar karena kepala rumah tangganya terjebak dalam candu yang mereka sebut “teman berpikir” dalam kehidupan.
Nurani yang Terbakar
Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), pengeluaran masyarakat kelas bawah untuk rokok berada di posisi kedua setelah beras. Ironi yang menjelaskan bahwa banyak rumah tangga berpenghasilan rendah dan di bawah rata-rata, uang untuk rokok justru lebih besar daripada untuk pendidikan atau gizi anak.
Baca Juga :
“Kemiskinan bukan hanya persoalan tidak punya harta, tapi juga tentang hilangnya kesadaran untuk menata hidup dengan lebih bijak dan bermanfaat.” – Ahaf
Barangkali inilah yang kini sebagian besar terjadi. Banyak kepala keluarga kehilangan kesadaran tentang tanggung jawab dan apa yang seharusnya menjadi prioritas.
Kalau kita hitung-hitungan angka, harga sebungkus rokok kini berkisar Rp20.000-Rp35.000. Jika seorang ayah dalam satu hari menghabiskan sebungkus rokok, maka dalam sebulan ia mengeluarkan Rp600.000-Rp1.000.000 hanya untuk asap yang dibuangnya di udara. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli lebih dari 30 kilogram beras, lauk sederhana bulanan bagi keluarga kecil, atau untuk uang SPP sekolah anak.
Simbol Kejantanan yang Salah Kaprah
Kebiasaan merokok telah lama dianggap sebagai sebuah simbol identitas sosial sebagai pria Indonesia. Tak sedikit yang berpandangan “bukan laki sejati” kalau tidak merokok. Mereka seperti beranggapan bahwa merokok adalah simbol kejantanan, padahal itu hanyalah sebuah simbol keterikatan.
“Kebiasaan akan membelenggu orang-orang yang lengah. Seseorang yang terikat akan dibawa ke tempat yang suram bernama gua keputusasaan” – Anonim
Kira-kira begitulah candu rokok bekerja. Yang diawal hanya teman santai, lama-lama malah jadi kebutuhan yang sulit untuk dilepas–bahkan ketika dapur tidak lagi berasap.
Perilaku konsumtif terhadap rokok di kalangan masyarakat kurang mampu tersebut bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga permasalahan sosial-psikologis. Tentang gengsi, solidaritas, bahkan syarat untuk dapat diterima di lingkungan sosial yang membuat rokok seperti kewajiban dan kebutuhan pokok hidup.
Keluhan Istri dan Anak di Balik Asap
Suatu waktu saya pernah berbincang dengan seorang ibu penjaga warung di pasar kecil di Kalimantan Tengah. Dengan wajah lelah, ia berkata “Kadang saya bingung, dek. Suami tiap pagi beli rokok, sedangkan beras di rumah habis. Kalau saya tegur, malah bilang saya cerewet.”curhatnya waktu itu.
Bagi banyak perempuan seperti ibu yang saya temui itu, asap rokok bukanlah aroma khas yang dapat menenangkan jiwa, melainkan sebuah tanda bahkan alarm yang mengingatkan bahwa ada perut anak-anak yang kosong. Mereka menjadi korban ganda: korban ekonomi sekaligus korban kesehatan.
Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) sedikitnya terdapat sekitar 34% anak di Indonesia terpapar asap rokok di rumahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman justru berubah jadi ruang ancaman bagi tumbuh kembang anak.
Antara Hak dan Tanggung Jawab
Sebagian lelaki mungkin akan berkata “merokok itu hak pribadi.” Betul, tapi setiap hak selalu datang bersamaan dengan tanggung jawab. Ketika hak itu menyampingkan bahkan melepaskan tanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga, maka ia tidak lagi menjadi hak, tapi sebuah beban moral.
Kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah bentuk lain dari kehancuran. Dalam konteks ini, kebebasan merokok bisa menjadi sebuah kehancuran secara perlahan bagi rumah tangga kurang mampu–bukan karena takdir, tapi karena pilihan.
Menjadi kepala keluarga bukan sekadar urusan menafkahi, tetapi juga tentang menata arah hidup keluarga ke jalan yang lebih baik. Anak tak membutuhkan ayah yang beraroma nikotin di bajunya, tapi sosok ayah yang memantik semangat hidup ditengah kesulitan. Istri tak butuh asap rokok, tapi butuh tanggung jawab untuk kehidupan yang layak.
Sebuah Renungan: Bara yang Sesungguhnya
Mari kita sejenak merenung: apakah benar rokok memberikan solusi, atau hanya menutupi rasa bersalah karena gagal menafkahi keluarga dengan layak? Apakah rokok benar-benar “teman”, atau justru musuh dalam dompet yang mencuri masa depan keluarga kita?
Ironisnya, banyak dari mereka para ayah yang menghisap rokok dengan bangga, tapi lupa bahwa anak-anaknya menghisap udara lapar dari perut yang kosong di ruang yang sama.
Menjadi lelaki sejati tidak diukur dari seberapa tebal asap rokok yang dihembuskan, tetapi seberapa kuat tekadnya menyalakan dapur untuk kebutuhan pokok keluarganya. Kejantanan bukan dari bara di ujung batang rokok, tapi pada bara tanggung jawab yang tak pernah padam.
Penulis: Ahmad Hasan Fatih, Pemimpin Redaksi Betang Voice dan Alumni Tempo Institute